Malam itu, ibu hampir membunuh adik. Aku tak begitu tahu sebab persisnya dan bagaimana kejadiannya karena sedang bermain di ruang tengah ketika bapak dan ibu beradu mulut di dapur.
Aku hanya datang menengok sebentar. Sempat kudengar dari mulut bapak yang berulang-ulang mengatakan bahwa ibu hampir saja membunuh adik. Mereka terus beradu mulut dengan sengit. Tak peduli adik bayiku yang terus menangis di balai-balai dapur.
Pertengkaran itu disudahi dengan masuknya ibu ke kamar tidur depan sambil masih bersungut, “Kalau kau pikir aku mau membunuhnya, sudahlah tak usah dia tidur denganku.”
Kami tak jadi makan malam itu, padahal makanan sudah tersedia di atas meja. Tinggal dilahap. Adik bayiku pun tidur bersama bapak di kamar belakang, sementara aku bersama ibu di kamar depan.
Besoknya pagi-pagi buta, diam-diam ibu berkemas. Aku sempat terbangun mendengar ibu sibuk sekali di dalam kamar, tidak seperti biasanya. Biarpun begitu, karena melihat di luar masih gelap, aku kemudian tertidur kembali.
Di dalam tidur yang singkat itu, aku sempat bermimpi. Bersama anak-anak tetangga, kami mengejar beberapa ekor anak babi yang lepas dari kandang. Samar-samar kudengar ibu sempat membangunkanku, “Nela, bangun! Kau mau ikut ibu tidak?”
Bagiku, suara ibu waktu itu begitu mengganggu dan mengesalkan. Aku ingat, aku hanya melenguh pelan dan tidak bergerak. Aku masih ingin melanjutkan mimpi, penasaran akan nasib akhir anak-anak babi itu, apakah mereka tertangkap atau tidak.
Namun, ibu tak henti-hentinya membangunkanku di antara kesibukannya berkemas. “Kalau kau mau ikut, cepat bangun dan berkemas! Kita harus berangkat sebelum bapak dan adikmu bangun.”
Hanya kalimat itu yang sempat kudengar dari ibu. Aku tak ingat apa-apa lagi sampai cahaya matahari menerpa jendela dan bapak masuk memanggilku segera bangun.
“Ibu tak ada di rumah,” kata bapak. “Kau jaga adikmu. Bapak mau pergi mencari ibu.”
***
Setengah jam kemudian, tampak ibu datang digiring bapak dari belakang. Rupanya ibu berencana pergi entah ke mana. Untungnya bapak bergerak cepat. Ibu tak jadi pergi, tetapi barang-barang yang sudah dikemasnya dalam tas kain tidak dikembalikan ke tempat semula.
Tas kain itu masih saja tergeletak di atas meja ruang tengah. Kupikir hari itu akan berjalan sebagaimana biasanya. Benar, nampaknya dari pagi hingga siang memang demikian. Kami sempat sarapan dan makan siang bersama.
Bapak dan ibu masih sesekali bicara saat perlu. Ibu masih sempat menyusui adik dan juga menyiapkan bubur sumsumnya. Namun, kira-kira pukul dua atau tiga sore, aku yang sedang bermain di halaman depan mendengar panggilan ibu.
Ia melambaikan tangan agar aku mendekat ke bawah jendela kamar tidur depan. Tepat di bawah jendela, ia menyodorkan tas kain yang sempat dikemasnya pagi tadi.
“Terima ini dan tunggu di situ. Ibu lewat pintu depan,” katanya lantas menutup kembali daun jendela.
Tak lama kemudian ibu muncul. “Kau mau ikut ibu atau tetap di sini?”
Bingung menjawab apa, ibu langsung menarik tanganku lalu kami keluar ke jalan besar. Aku ikut saja, bahkan tak sempat melepaskan piring tempurung kelapa yang sebelumnya kupakai bermain masak-masakan.
Aku menoleh kembali ke rumah. Tak tampak siapa-siapa. Tentu, adikku pasti sedang tidur di kamar belakang, sementara bapak ada di pekarangan samping, menggergaji dan mengetam beberapa potong kayu pesanan orang.
Karena ia berada di samping rumah bagian selatan, ia tak bisa melihat kami yang mengarah ke utara. Hari masih begitu terik., jalan besar sepi. Kami tak berpapasan dengan seorang pun hingga memasuki jalanan setapak yang di samping kiri-kanannya penuh semak belukar.
Kata ibu, kami pergi ke rumah sepupunya di kampung tetangga. Kampung itu biasanya ditempuh lewat jalan besar dengan bus, truk, bemo, pick up, atau sepeda motor, bahkan bisa berjalan kaki.
Akan tetapi, perjalanan aku dan ibu kali itu tidak melewati jalan besar seperti pada umumnya. Ibu malah memilihkan jalan baru lewat kebun dan ladang orang.
“Biar tidak ada orang kampung kita yang melihat,” katanya.
Kami menempuh perjalanan berkilo-kilo tanpa henti. Perjalanan kami pun tidak melulu jalanan datar. Karena kampung kami berada di daerah pesisir pantai, perjalanan kami keluar kampung selalu mendaki.
Jalan yang datar hanya ada beberapa meter kemudian kembali mendaki, mendaki, dan terus mendaki. Sepanjang jalan aku terus berlari demi mengimbangi langkah kaki ibu yang panjang.
Setiap kali aku berusaha mendahului agar bisa beristirahat sambil menunggu, ibu selalu sampai tepat aku baru mau berhenti. Sudah begitu, bukannya berhenti sejenak agar membiarkanku mengambil napas, ia malah terus mengayunkan langkah panjangnya.
Dengan demikian, mau tak mau aku harus kembali mengejar dan berusaha mendahului untuk kemudian didahului lagi. Berkali-kali seterusnya begitu hingga aku merasa letih sekali. Betapa sebuah kebahagiaan tak terkira seandainya kami berhenti sejenak dan kerongkonganku yang kering itu dibasahi seteguk air.
Begitu kubilang pada ibu tentang air, ia justru balik memelototkan matanya, membentak menyuruh diam dan mengancam akan meninggalkanku seorang diri.
Karena itu, meski napasku hampir habis, tinggal satu-satu, dan kerongkonganku seperti terbakar, kukuatkan diri terus berlari dan tak lagi mengeluh. Tak mau aku ditinggal ibu sendirian di tengah-tengah belantara ini.
Adik bayi yang masih delapan bulan saja hampir ia bunuh, apalagi meninggalkan seorang anak perempuan yang sebentar lagi masuk TK. Membayangkan sebentar lagi masuk TK, semangatku kembali hidup. Aku memang sering mencuri dengar pembicaraan bapak dan ibu serta tetangga-tetangga.
Kata mereka, tahun ini aku akan bersekolah. Senang sekali rasanya menjadi anak sekolah. Pikiran tentang sebentar lagi masuk TK inilah yang mendorongku penuh semangat terus berlari mengimbangi langkah panjang ibu.
Hari sudah mulai gelap ketika kami akhirnya keluar di jalan besar. Tampak rumah-rumah orang berjejer sepanjang jalan. Lampu-lampu rumah sudah mulai menyala, kecuali jalanan yang masih tetap gelap.
Rasanya aku ingin memasuki sembarang rumah dan meminta sedikit air. Kerongkonganku tak kuat lagi kutahan. Kuberanikan diri bicara pada ibu, mengutarakan niat meminta air.
”Tidak usah,” ia melarang. “Sebentar lagi kita tiba.”
Kalimat tentang sebentar lagi itu rasanya setahun. Perjalanan ternyata masih panjang. Masih berupa dakian yang tak berujung. Tak ada jalanan rata, apalagi jalanan menurun sejak kami keluar di jalan besar.
Rumah demi rumah kami lewati. Mungkin belasan atau puluhan. Sebagaimana perjalanan kami sebelum keluar di jalan besar, aku masih saja selalu tertinggal di belakang ibu. Tepat di bawah satu tanjakan yang sempat kukira kalau aku harus mendakinya sekali ini lagi maka aku akan mati, tiba-tiba ibu berhenti.
Ia berpaling ke arahku, menungguku yang sedang berlari mengejarnya dan segera menangkap pergelangan tanganku. Sejenak ia menunduk lalu menatap mukaku dalam gelap.
“Apapun yang mereka tanyakan, jangan kau beritahu!”
Aku tak menjawab, bahkan untuk mengangguk pun, aku tak sanggup. Ibu menarikku masuk ke sebuah gang di sebelah kiri tanjakan. Kira-kira sepuluh meter, kami berbelok ke kanan dan memasuki sebuah pekarangan. Ibu mengetuk pintu dan memberi salam.
“Tante Lisa,” sebuah sapaan datang dari seorang anak perempuan yang membuka daun pintu bagian atas. “Dengan Nela juga ternyata,” ia berseru kaget melihatku ketika membuka seluruh daun pintu.
Kami berdiri kaku di depan pintu yang sudah dibukakan. Pergelangan tanganku masih dipegang erat ibu, padahal aku ingin segera lepas dan meminta air.
Sepupu ibu yang kupanggil Om Tom muncul ketika mendengar siapa yang datang. Istrinya dan anak-anak mereka yang lain pun berdatangan. Mereka heran dan takjub mendengar sepanjang jalan dari rumah aku hanya berjalan kaki.
Segera salah satu anaknya mengajakku ke dapur dan memberi minum. Sambil meneguk air, aku sempat ingin mengatakan bahwa sepanjang jalan aku terus berlari tanpa henti, tapi segera kutahan karena mengingat pesan ibu.
Kami ikut makan malam bersama keluarga Om Tom. Sesudah itu, aku tidur bersama dua anak perempuannya.
Menjelang tidur, aku baru teringat akan mimpiku pagi harinya. Bersama beberapa anak-anak tetangga, kami mengejar anak-anak babi yang lepas dari kandang. Nyatanya, sepanjang sore ini aku berlari mengejar ibu yang diam-diam pergi dari rumah.
***
“Kuminta kau berterus terang. Sebenarnya kalian datang ke sini dalam rangka apa?” Om Tom bertanya pada pagi hari berikutnya ketika ibu baru saja pulang dari pancuran ikut membantu para keponakannya mengangkat air.
“Tidak dalam rangka tertentu,” ibu menjawab sambil menuangkan air dari ember yang dipikulnya ke dalam drum penampung. “Hanya ingin berkunjung.”
Aku mendengar percakapan itu, tapi terus sibuk memainkan karet-karet gelangku. “Bagaimana dengan Adibu?” Om Tom melanjutkan pertanyaannya.
“Baik-baik saja dengan bapaknya,” jawab ibu terus sibuk menata ember-ember kosong.
Aku tahu ibu berbohong, tapi aku diam. Apapun yang dikatakannya bukan urusanku selama aku baik-baik saja hingga nanti tiba pendaftaran masuk TK, aku akan ikut didaftarkan.
Aku kurang ingat berapa malam kami menginap di rumah Om Tom. Satu hal yang terekam jelas dalam kepalaku adalah aku tak punya pakaian ganti sendiri selama aku berada di rumah Om Tom sehingga aku harus menyesuaikan diri dengan pakaian para sepupu perempuanku yang kebesaran.
Suatu hari ketika bangun pagi-pagi, sepupu perempuanku yang tertua menyambutku dengan satu tas kecil yang tak sempat kutengok apa isinya. Ia berpesan, nanti gantian di hari libur sekolah, mereka yang akan mengunjungiku.
Sambil mengucek mata, aku melangkah ke ruang tamu. Di sana, duduk dua orang pemuda yang kukenal berasal dari kampung kami. Di bahu mereka masing-masing tersampir selendang bahan tenunan.
“Om mau ke kampung kalian,” kata Om Tom begitu ia muncul dari ruang tengah sambil berkemas. “Ini haef* dari sana. Ada berita duka. Bukan di rumah kalian tentunya, tapi kau dan ibumu sekalian ikut saja. Kita berangkat sama-sama.”
Meski agak berat hati karena sudah harus berpisah dengan keluarga Om Tom, terutama dua anak perempuannya yang di sela-sela waktu bermain, sering mengajakku belajar mengeja huruf dan berhitung, jauh di dalam hatiku ada juga rasa girang.
Sebentar lagi kami kembali ke rumah. Tak sabar aku ingin bertemu adik dan bapak yang entahlah sedang buat apa di sana. Aku mencoba mengingat-ingat wajah adik bayiku saat terakhir kulihat sebelum meninggalkan rumah, pagi itu ketika disuruh bapak menjaganya sementara bapak pergi mencari ibu.
Dalam perjalanan pulang pagi itu, kami lebih banyak diam. Tingkat kesulitannya tidak sepayah perjalanan datang. Selalu menurun. Aku pun tak harus selalu berlari karena sesekali Om Tom menggendongku di pundaknya.
Memasuki gerbang kampung yang ditandai tugu buatan para mahasiswa yang pernah datang melaksanakan KKN, aku meminta diturunkan agar bisa berlari sendiri menuju rumah. Jalanan menurun begitu apa susahnya. Sambil berlari aku membayangkan melihat bapak berdiri di depan rumah kami, menggendong adik, serta tersenyum gembira menanti kepulangan kami.
Harapanku yang menggebu buyar seketika melihat begitu banyak orang dewasa tampak sibuk persis di halaman rumah kami. Ada yang memotong beberapa tanaman di depan rumah, ada yang mendirikan pasak, sebagian lagi menebarkan terpal, dan sisanya mengatur kursi-kursi.
Dengan rasa ingin tahu dan kepala penuh tanya, aku terus mendekat. Seseorang di antara yang sibuk itu tiba-tiba melihatku. Seketika ia melepaskan pekerjaannya. Dengan sekali gerak, ia berlari datang ke arahku.
Belum sempat aku menyadari apa yang terjadi, ia sudah meraihku dan menggendong masuk ke dalam rumah. Dari bahu orang itu, kulihat jauh di belakang sana, Om Tom memapah ibu yang sudah histeris tak karuan. Di dalam rumah itulah baru aku tahu, adik bayiku sudah terbaring kaku di tempat tidur dan sementara ditangisi bapak dari pinggirannya.
Catatan:
*Haef dalam bahasa Dawan berarti kaki. Sebutan ini kerap ditujukan khusus kepada orang- orang yang diutus pergi menyampaikan kabar suka/duka kepada sanak saudara, handai tolan, dan kenalan di berbagai tempat yang jauh dengan berjalan kaki, menunggang kuda, atau mengendarai sepeda motor.
Sebuah karya cerpen berjudul ‘Meninggalkan Adik’ oleh Anacy Tnunay yang diperlombakan dalam lomba menulis cerpen fajar pendidikan.


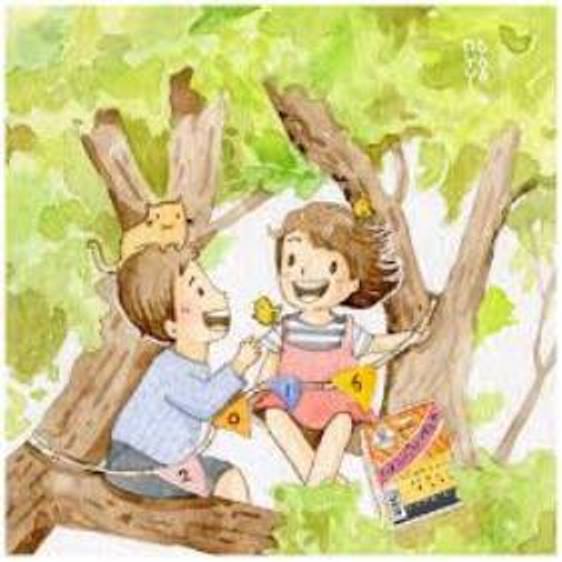

 Penulis: Tiara Fanisa
Penulis: Tiara Fanisa







